
Dengan adanya ideologi
kapitalisme sistem pendidikan telah dibentuk seperti sistem pasar, dimana
penawaran (supply)
dan permintaan (demand)
bertemu dan bertransaksi. Pendidikan
menjadi barang dagang yang dibutuhkan (need) dan dengan
posisi tersebut harga menjadi tandingan dari sebuah kebutuhan. Penyedia
pendidikan dengan jaminan pemenuhan kebutuhan dapat menentukan harga yang
dianggap berimbang dengan jaminan tersebut.
Maka pendidikan yang merupakan kebutuhan wajib untuk membekali diri dalam menghadapi realita hidup, diinterpretasikan melalui sekolah formal. Akibatnya adalah peserta didik diposisikan sebagai objek yang mesti dijejali dengan ilmu pengetahuan yang dipaketkan, serta mesti mengikuti segala tata aturan yang ada di sekolah, termasuk keharusan membayar uang admnistrasi sekolah. Dan tentu saja, sekolah formal yang merasa di atas angin, dengan kualitas pengajaran yang mereka punya, apalagi dengan permintaan para orang tua murid dengan grafik pasar meningkat, cenderung untuk menaikkan pembayaran sekolah dengan berbagai kedok seperti uang pembangunan gedung dan fasilitas dll.
Kondisi seperti ini melahirkan
kastanisasi pendidikan, dimana pada beberapa sekolah maju dengan uang pangkal
pendaftaran yang juga tinggi dan pembayaran SPP selangit, kebanyakan dihuni
oleh siswa yang orang tuanya berada pada ekonomi menengah ke atas. Sementara
pada sekolah pinggiran, dengan minim fasilitas dan kebanyakan dihuni oleh siswa
yang orang tuanya berada pada ekonomi menengah ke bawah. Belum lagi, jika kita
singgung bagaimana rakyat miskin yang jangankan untuk menyekolahkan anaknya
pada sekolah bergengsi, untuk bertahan hidup sehari-hari pun sangat sulit.
Padahal pendidikan adalah sebagai proses
humanisasi (Paulo freire), bagaimana karakter seseorang dibentuk berdasar pada
pengalaman dan pengetahuan yang didapatnya. Dari proses pendidikanlah kemudian
nilai-nilai moral dan kepemahaman mengenai proses produksi yang menempatkan
manusia sebagai pelaku. Adalah sebuah ironi ketika pendidikan sebagai proses
untuk memanusiakan manusia justru mengabaikan apa yang mesti menjadi
prioritasnya. Dari sana terlihat bahwa urgensi pendidikan nyatanya telah
bergeser dari proses memanusiakan manusia menjadi lahan untuk mencari
untung yang mencitrakan pengabaian hak asasi manusianya.
Dalam segala bentuk kastanisasi pendidikan ini,
negara punya peran vital paling tidak untuk meminimalisir adanya
pengkotak-kotakan masyarakat berdasarka tingkat perekonomiannya. Apalagi
negara, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi,
“mencerdaskan kehidupan bangsa”, punya kewajiban agar pendidikan bisa dicicipi
oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Di sepanjang kemerdekaan
Indonesia yang sudah tidak bisa dibilang muda, kiranya miris melihat fakta bahwa
kastanisasi pendidikan masih tumbuh subur. Kita sudah kenyang dengan
kastanisasi pendidikan pada zaman kolonial belanda, dengan adanya sekolah
rakyat dan sekolah priayi. Beberapa kali pergantian sistem pendidikan, tidak
berpengaruh banyak guna meminimalisir kesenjangan ini.
Terkait akan peran starategis negara, maka
baru-baru ini ramai dibicarakan tentang kebijakan pemerintah sebagai pembuat
kebijakan tentang standarisasi sekolah, dalam hal ini sekolah berstandar
internasional. Gonjang- ganjing ini terbagi pada dua kubu, yaitu kubu yang pro
dan kontra perihal diterapkannya standarisasi internasional.
Dan tentu saja tiap kubu punya argumentasi
masing-masing akan hal ini. Dengan menerapkan standarisasi sekolah, akan dapat
menciptakan iklim persaingan guna meningkatkan mutu pendidikan baik itu dalam
iklim belajar, pemberdayaan siswa, maupun fasilitas penunjang yang mumpuni.
Bacaan sementara pemerintah adalah minimnya mutu pendidikan jika
diperbandingkan dengan menggunakan kacamata internasional. Ada semacam ketertinggalan
yang menyebabkan Indonesia kalah bersaing dengan dunia internasional, termasuk
dalam penguasaan bahasa internasional yakni bahasa inggris. Maka Icon
SBI terbentuk berdasar pada penerapan bilingual sebagai medium of
instruction, multimedia dalam pembelajaran di kelas, ataupun sebagai
sekolah prestisius dengan jalinan kerjasama antara Indonesia dengan
negara-negara anggota OECD maupun lembaga-lembaga tes/sertifikasi
internasional, seperti Cambridge, IB, TOEFL/TOEIC, ISO, dan lain-lain. Statement
ini diperkuat dengan penggunaan bahasa inggris sebagai bahasa pengantar dalam
sekolah SBI berdasar pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Pasal 50 Ayat 3. Dalam ketentuan ini, pemerintah didorong
untuk mengembangkan satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
Sebelum menuju SBI, proses yang dilakukan adalah
akreditasi sekolahan untuk memprogramkan Rintisan Sekolah Bertaraf
Internasional (RSBI). Mengacu pada UU Sikdiknas No. 22 Tahun 2003 terutama pada
pasal 50 ayat 3, peraturan pemerintah dalam pasal 61 ayat 1, rencana strategis
pendidikan nasional tahun 2005–2009, RSBI adalah kebijakan pemerintah dengan
menerapkan konsep sekolah berbasis ICT (Information Communication and
Technology). Dengan alokasi dana sebesar 15 miliar termasuk dari APBD untuk
setiap sekolah di daerah-daerah.
RSBI justru mengundang perdebatan karena jika
dilihat dari nilai-nilainya, RSBI mengutamakan kompetisi untuk meningkatkan
mutu pendidikan. Pemerintah yang seharusnya membantu sekolah meningkatkan mutu
pendidikan justru mendorong setiap sekolah untuk bersaing satu sama lain.
Padahal, dari nilai-nilai Pancasila tidak disebutkan kata-kata persaingan, yang
ada yaitu nilai-nilai kerja sama dan kebersamaan. Seolah-olah sekolah harus
bersaing untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam kompetisi skala besar,
meniscayakan adanya usaha-usaha pencapaian dan siapa yang dapat menjamin jika
usaha yang dilakukan bukanlah usaha simbolik yang non substansi pendidikan.
Permasalahan mendasar dari RSBI terletak pada pemberian
ruang yang lebar bagi kemungkinan terjadinya kapitalisasi pendidikan di setiap
penyelenggaraannya, karena, RSBI mendorong kastanisasi dan antidemokrasi.
RSBI
justru mendorong konsep privatisasi pendidikan semata-mata karena anggaran
minim dari pemerintah. Untuk menjawab masalah anggaran, pemerintah justru
dorong privatisasi pendidikan melalui RSBI. (Source : Kompas, Senin, 21
Juni 2010 | 04:41 WI)
Dengan perangkat pendidikan yang terbilang mahal
akan berimplikasi pada mahalnya biaya untuk menjadi salah satu peserta didik.
Argumentasinya adalah untuk menutupi kekurangan anggaran dan penambahan
fasilitas penunjang pendidikan yang memiliki standar tinggi dengan jaminan
kualitas. Sehingga, setiap manusia yang diwajibkan oleh pemerintah agar wajib
sekolah sembilan tahun, namun, terkendala oleh biaya yang mencekik tidak mampu
untuk bersekolah di semua sekolahan-jika semua sekolahan yang ada di Indonesia
berhasil mencapai SBI. Pemerintah mewajibkan semua orang untuk bersekolah,
namun kebijakan pemerintah sendiri jika dilirik dalam jangka panjang berkesan
kontradiktif.
Bercermin dari SBI di Malaysia, bahwa SBI
bukanlah pilihan yang tepat. Malaysia terbukti gagal dengan SBI-nya. Pemerintah
Indonesia tidak juga mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain tersebut.
Permasalah dari SBI itu sendiri adalah, standar mana yang bisa dikatakan
sebagai standar Internasional ? sedangkan negara lain punya satandarnya
masing-masing, karena, selama ini memang tidak ada kurikulum pendidikan yang
dibahas oleh semua negara untuk dapat dijadikan standar Internasional.
Jika dihayati secara hikmat dengan bertitik tolak
dari hakikat keberadaan Negara yaitu, “melindungi setiap hak asasi manusia”
. Serta amanat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu “…ikut mencerdaskan kehidupan
bangsa...”, adalah sebuah ironi jika dihadapkan pada kondisi pendidikan di
Indonesia pada saat ini. Pendidikan adalah hak asasi manusia untuk
memperolehnya. Kebijakan yang memberikan celah untuk terjadinya kastanisasi dan
pengkotak-kotakan antara yang kaya dan yang miskin dalam hal kelayakan
mendapatkan pendidikan dari pihak penyelenggara pendidikan adalah perampasan
terhadap hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan itu sendiri.
Pada akhirnya dalam proses pendidikan hal
terpenting bukan pada simetrisasi antara kualitas predikat output dari
sebuah lembaga sekolah dan dana logis yang sepadan, tetapi, permasalahannya ada
pada keberpihakan terhadap yang benar-benar tidak mampu. Kualitas tidak perlu
mengakreditasikan dirinya sebagai sesuatu yang memiliki standart tinggi, tetapi
bukti kongkrit untuk sebuah kesejahteraan. Ini lah budaya kulit yang
dikampanyekan oleh kapitalisme. Sedangkan dilain pihak mindset yang selama ini
terbangun adalah, masih banyak orang berpendidikan formal yang “menganggur”
sehingga, orang yang tidak punya biaya untuk pendidikan akan lebih memilih
bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk apa sebuah predikat, jika
hanya melahirkan kesempatan bagi kapitalis dan komersialis untuk meraup
keuntungan dan menciptakan kasta-kasta dalam pendidikan dan serta tidak
egaliter.
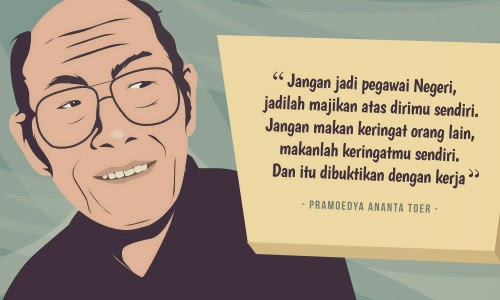
Tidak ada komentar:
Posting Komentar